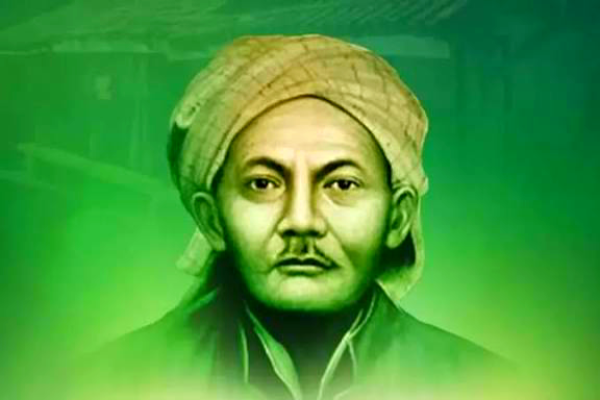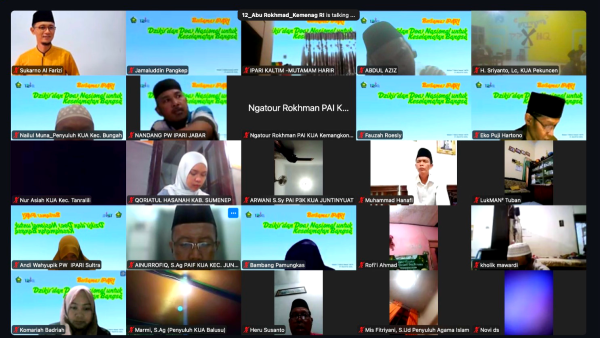SURABAYA, PustakaJC.co - Pondok pesantren telah menjadi mercusuar peradaban Islam Nusantara selama ratusan tahun. Di lingkungan inilah ilmu para ulama diwariskan, adab dibentuk, dan akhlak ditanamkan. Pesantren bukan sekadar tempat mengaji kitab kuning, melainkan ruang pembentukan jiwa dan karakter yang tak selalu bisa ditemukan dalam model pendidikan modern.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, muncul arus opini dan pernyataan publik yang berpotensi mengusik marwah pesantren. Setelah sempat mencuat kontroversi dari tayangan Xpose UncensoredTrans7, kini sejumlah pernyataan kembali menimbulkan kegaduhan di ruang digital. Dilansir dari nu.or.id, Kamis, (20/11/2025).
Salah satunya datang dari KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengenai istilah “kibin baalawi” yang ia gunakan untuk menilai kiai tertentu. Istilah tersebut tidak dikenal dalam literatur keilmuan, tidak ditemukan dalam kitab fikih, tasawuf, ataupun kamus klasik Arab. Pemakaian istilah yang tidak jelas itu justru memunculkan stigma dan mendorong opini negatif terhadap kiai yang dekat dengan habaib.
Tak lama berselang, muncul pula pernyataan Kiai Nur Ihya yang meragukan kualitas Pesantren Lirboyo dan mengimbau orang tua untuk memindahkan putra-putrinya. Meski disampaikan sebagai pandangan pribadi, narasi semacam ini dengan cepat menyebar dan memicu kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Dalam tradisi pesantren, kehormatan ulama, habaib, dan dzurriyat Nabi Muhammad SAW dijunjung tinggi. Kedekatan para kiai dengan habaib telah menjadi bagian dari transmisi ilmu, adab, dan silsilah keilmuan sejak masa para pendiri pesantren. Karena itu, penyudutan terhadap kedekatan tersebut bukan hanya menunjukkan minimnya pemahaman sejarah, tetapi juga mengaburkan nilai adab yang diwariskan para masyayikh.
Narasi semacam ini bekerja secara halus—melalui istilah baru yang provokatif, pengulangan opini yang tidak ilmiah, dan fragmentasi informasi. Ketika sebuah istilah terus diulang dalam ruang publik, perlahan ia membentuk persepsi baru. Jika tidak diimbangi dengan literasi keilmuan, masyarakat bisa terjebak pada opini yang tidak berdasar.
Pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Sarang, dan lainnya kerap menjadi sasaran karena memiliki jaringan alumni luas, pengaruh sosial kuat, dan jejak historis panjang. Menyerang reputasi lembaga-lembaga ini dapat menjadi cara cepat untuk menggeser peta pengaruh keagamaan. Kritik memang wajar, tetapi framing negatif yang viral dapat menimbulkan kesimpangsiuran dan membangun keraguan publik secara tidak proporsional.
Ketika muncul narasi seperti “jangan mondok di kiai tertentu karena bisa jadi budak”, itu bukan sekadar kalimat provokatif, melainkan bentuk delegitimasi terhadap otoritas keilmuan. Dalam tradisi ulama, menjatuhkan martabat guru sama artinya dengan merusak mata rantai ilmu. Publik diarahkan menjauhi ulama bersanad jelas, lalu mengikuti figur yang belum tentu memiliki dasar yang kuat.
Jika pola semacam ini dibiarkan, standar keilmuan bisa bergeser. Fanatisme tokoh, kultus individu, dan fragmentasi umat menjadi ancaman yang nyata. Padahal pesantren telah lama mengajarkan adab perbedaan, penghormatan antarulama, dan penjagaan sanad keilmuan.
Pesantren tetap kokoh. Di tengah arus opini yang berubah-ubah, pesantren terus berperan menjaga warisan ilmu, memperkuat pendidikan akhlak, serta menjadi ruang aman bagi tumbuhnya generasi beradab. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren tetap kuat, ditopang oleh sejarah panjang, kualitas pendidikan, dan kontribusi nyata bagi umat.
Umat perlu lebih bijak dalam membaca narasi. Jangan mudah terpancing isu yang tidak memiliki dasar ilmiah. Kembalilah merujuk kepada kiai yang jelas sanadnya, teruji adabnya, dan nyata perjuangannya. Pesantren adalah warisan emas para ulama—selama pesantren tegak, tradisi keilmuan Islam Nusantara akan tetap kokoh. (ivan)